KISAH penyadapan Australia terhadap pejabat negara Indonesia masih belum usang. Masing-masing negara mempertahankan argumentasi. Ind...
KISAH penyadapan Australia terhadap pejabat negara Indonesia masih belum
usang. Masing-masing negara mempertahankan argumentasi. Indonesia sebagai
negara hukum, menilai tindakan dinas intelejen Australia pada Agustus 2009
telah melanggar hukum dan mencederai demokrasi.
Kini, sejumlah kerjasama antara negara Indonesia dan Australia ditinjau
ulang. Baik dalam bidang keamanan hingga perdagangan. Australia enggan untuk
meminta maaf terhadap Indonesia. Meski menganggap bahwa hubungan Indonesia dan
Australia tak ada persoalan, mereka tetap tidak mau meminta maaf atas sekandal
penyadapan terhadap pejabat negara seribu pulau.
Bagi saya, penolakan PM Australia Abbott untuk meminta maaf terhadap
Indonesia hanya karena merasa malu dengan Indonesia. Sebab, dia barangkali
berprinsip bahwa orang yang meminta maaf atas kesalahan diri dianggap lemah.
Hakikatnya, saya yakin, mereka mau meminta maaf karena sudah melanggar hukum
demokrasi.
Meminta maaf memang kedengaran sangat mudah dan gampang. Tetapi, jika
permohonan maaf disampaikan didepan umum, publik Australia atau dunia
Internasional, tentu akan merasa malu. Mereka mungkin khawatir dianggap sebagai
negara lemah dan tak kuasa. Gitu aja udah minta maaf. Power negara sebagai
pengimpor pangan terbesar ke Indonesia akan menjadi lemah.
Barangkali, mengaku salah, meminta maaf, dan merendahkan hati dan serta
mau melemaskan sikap arogansi sulit terjadi. Jangankan seorang perdana menteri,
orang biasa-biasa saja juga sulit untuk meminta maaf terlebih dahulu ketika
salah. Mereka selalu benar. Benarnya sendiri. Mungkin saja mereka berfikir,
meski akan meminta maaf tak mungkin Indonesia akan memafkan tindakan buruk
mereka.
Ah, rasanya terlalu jauh saya berbicara negara Indonesia-Australia. Saya
bukan ahli tata hukum negara. Saya tidak tahu persoalan hubungan antar negara.
Yang saya tahu, hanya apa yang saya lihat dan yang saya dengar saja. Tak
banyak. Beberapa bagian saja. Setelah itu, hanya menilai Australia mungkin lagi
gengsi jika harus meminta maaf. Egoisme kenegaraan tentu akan dimiliki setiap
negara.
Ketika saya masih sekolah di desa-desa di Madura, atau propinsi lain di
Jawa Timur, hanya belum menemukan guru SD atau SMP mengajar lulusan S3 atau
bergelar doktor. Meski ada, hanya sebagian saja. Itupun titel hasil membeli.
Bukan kuliah atau penelitian resmi.
Di desa saya, guru S1 masih bisa dihitung dengan jari. Justru yang banyak
alumni SMA mengajar SD. Lebih parah lagi, lulusan SD mengajar MI. Lulusan SMA
mengajar SMP. Ah, sungguh merendahkan hati dan mau mengajar ditempat siswa
sekolah berumur 15 tahun sulitnya minta ampun di negeri ini.
Sebenarnya bukan tidak ada alumnus S3 alias doktor di Indonesia. Bahkan,
pelamar dosen, harus antri. Mungkin lebih baik antri dibandingkan dengan
mengajar MI. Tak level dan bukan kelasnya. Kelas doktor menimal dosen. Bukan
guru.
Berkaca pada itu samua, saya teringat seorang teman yang kini menjadi
pejabat negara. Awalnya, dia adalah seorang guru Sekolah Dasar. Itu pun
statusnya sebagai guru sukwan (sukarelawan). Tetapi, pada akhirnya dia terpilih
menjadi anggota dewan melalui salah satu partai besar di Negeri ini. Menjadi
anggota dewan sangat terhormat. Menjadi pegawai negeri sudah terhormat, harus
dihormati bukan melayani.
Setelah jabatan belum mencapai puncak, dia telah lebih awal berhenti mengajar.
Dia tak mau lagi mendidik anak-anak yang masih ingusan. Tak mau lagi bersama
dengan siswa yang kadang kentut di depan gurunya. Masak pejabat tinggi negara
dikentuti anak masih tak tau apa-apa. Gengsilah !
Saya kemudian menjadi terharu dengan kisah Perdana Menteri Belanda Mark
Rutte. Kita memang pernah memiliki kisah buruk dengan Belanda. Tetapi, kisah
buruk itu sudah tiada. Karena Indonesia sudah (akan) merdeka. Penjajahan fisik
sudah sirna. Langkah yang dilakukan oleh PM Belanda tak perlu dicontoh, cukup
dijadikan sebagai pelajaran saja.
Mark Rutte, meski memiliki jabatan tinggi sebagai Perdana Menteri (PM),
setiap hari Kamis selalu mengajar anak-anak di sekolah berusia 14-15
tahun. Awalnya, dia mengajar pada setiap
hari Jumat. Tetapi karena pertemuan dewan selalu hari Jumat, jadwal mengajarnya
pun dirubah hari Kamis. Perdana Menteri bersama dengan anak-anak usia SMP di
Den Haag.
Mungkin saja, PM Belanda Mark Rutte juga memiliki rasa gengsi untuk
mengajar anak usia SMP. Tetapi, rasa gengsi itu menjadi sirna dengan rasa
tanggung jawab untuk mencetak generasi bangsa lebih baik dan mandiri. Dia
mungkin saja, dengan mengajar siswa SMP bisa mentransformasikan ilmu
kenegaraan. Dia tak gengsi mengjar siswa SD.
Sikap kesederhanaan ini sebenarnya dimiliki setiap orang. PM Australia
Abbott tidak mau meminta maaf karena egoisme diri, malu dan sombong. Mungkin
memang tak jauh beda dengan warga negara Indonesia. Doktor, Insinyur bukan tak
memiliki keinginan untuk mengajar siswa SD tetapi karena rasa gengsi berlebihan,
mereka enggan untuk mengajar. Muncul istilah; tak level.
Sampai kapan pendidikan Indonesia akan maju, jika tenaga pendidik berkelas
doktor enggan untuk mengajar siswa SD. Padahal, seumuran itulah yang akan
menentukan masa depan anak itu. Gengsi tak lebih dari kesombongan yang
menjijikkan. (*)
BUSRI TOHA
BUSRI TOHA





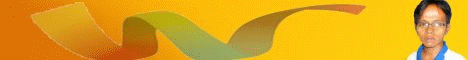


KOMENTAR