”Guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan Dewa dan selalu benar, dan murid bukan kerbau”. ITULAH sala...
”Guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah.
Guru bukan Dewa dan selalu benar, dan murid bukan kerbau”.
ITULAH salah satu
bait yang saya tangkap dari film Gie. Sebenarnya, saya ingin berlama-lama
hingga tuntas nonton film tahun 2005 itu. Bukan
karena saya tidak pernah menonton. Pada tahun 2007 silam, saya pernah nonton
bersama dengan teman-teman mahasiswa di Komisariat PMII Guluk-Guluk, Sumenep.
Tapi waktu itu, saya belum suka nonton film. Kini, bertepatan dengan HUT PGRI
ke-68, ingin nonton kembali film yang disutradarai Riri Riza, dan dibintangi
Nicholas Saputra yang berperan sebagai Soe Hok Gie.
Selasa malam saya menonton ulang film itu. Namun,
tak selang beberapa lama listrik PLN Sampang kembali mati. Akhirnya, teman saya
Fandri Ardiyansyah (Direktur sekaligus redaktur Suara Madura) setelah mendapat
instruksi dari Direktur Utama Suara Madura mengontak petugas dari PLN. Selain
memang listrik sering padam, kali ini bukan karena dari PLN padam tapi karena
konsleting listrik pada spidu meter.
Soe Hok Gie dilahirkan di Djakarta, 17 Desember 1942 dan
meninggal di Gunung Semeru, 16 Desember 1969 ketika masih berumur 26 tahun.
Saya tidak begitu tahu tentang Soe Hok Gie. Buku catatan harian dia ”Catatan
Harian Sang Demonstran” sudah tidak ada pada saya lagi. Dipinjam teman lalu tak
kembali.
Selama ini, guru selalu disanjung, dipuja dan dipuji. Guru
adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Begitulah bahasa yang selalu dilontarkan
untuk memuji dan menghormati guru. Apalagi, pemahaman kita guru harus dihormati
dan bahkan apapun perintahnya adalah kewajiban yang tak bisa dibantah. Seakan
titah guru adalah firman suci.
Sebaliknya, posisi murid atau siswa adalah objek. Murid
harus mengikuti titah guru. Kebenaran ada ditangan guru. Murid tidak boleh
membantah. Mengelak perintah guru adalah penghiatan. Instruksi guru adalah
perintah raja. Jika menolak titah guru, nilai akan dikurangi, tidak naik kelas
atau bahkan akan mendapat kekerasan, pukulan dan tamparan.
Suatu ketika sewaktu saya duduk di bangku sekolah SMA,
saya memiliki teman kritis dan memiliki kemampuan diluar kemampuan teman-teman
sekelas. Paling tidak, lebih cerdas dan pintar dibandingkan dengan saya. Setiap
materi yang disampaikan oleh guru tidak sesuai dengan pikiran dia, pasti akan
diprotes.
Namun, ke kritisan dia menjadi hilang setelah pada nilai
ujian anjlok, jeblok dan turun drastis. Dengan kecerdasan dan kekritisannya,
dia telah mempermalukan guru dalam kelas. Dasar guru pendendam, akhirnya nilai
hasil ujian kelas pada raport turun. Angka 9 menjadi 6. Semua materi pelajaran
yang dipegang dia, nilai ujian menjadi turun.
Akhirnya, teman saya tadi tak lagi berani memberontak, tak
lagi cerdas dan tak lagi menyangkal dengan titah guru. Semua kata guru dia
ikuti. Nah, kini nilai ujian di raport kembali naik. Sikap lugu telah
menyebabkan nilai ujian pelajaran menjadi lebih baik.
Sikap berani membrontak pada kesewenang-wenangan, pada
diri teman saya hilang. Sikap kritis yang selama ini tertanam, telah tumpul.
Selain tumpul karena sifat dirinya yang bukan pemberani, juga telah ditumpulkan
oleh guru kelasnya. Barangkali, dia lupa dengan Presiden Soekarno bahwa
Indonesia menjadi bebas dan Merdeka karena keberanian Soekarno melawan
penjajah, melawan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.
Tetirah dari sang guru bukan lagi mengispirasi, sebaliknya
justru menumpulkan daya imajinasi, kreatifitas. Guru berubah menjadi tongkat
pukul atau penggaris yang membuat tangan merah. Lebih dari itu, menjadi semacam
hantu menakutkan yang memaksa murid berselimut menggigil di kolong tempat
tidur.
Lantas apa guna murid dengan keriangannya berangkat ke
sekolah membawa bulpoin, kertas dan gundukan cita-cita untuk dihaturkan ke
guru? Barangkali guru perlu belajar mengidentifikasi ke-guru-annya, karena daya
tawar guru bisa menjadi penyakit yang tumpul dan memandulkan. Buang saja kurikulum
basi yang tak layak konsumsi itu, resapi masing-masing keunikan murid dan
katakan, ”selamat datang para pelopor” seperti guru Laskar Pelangi. Guru bukan
tumpukan buku berdasi dan bergincu menor.
Saya teringat kalimat Pramoedya yang tua itu, ”Seorang
terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam
perbuatan,” sungguh manis bukan. Secara sederhana saya pahami bahwa kejujuran
Pram tersebut harus dicecap baik-baik oleh guru sebagai manusia yang
berpendidikan. Adil dalam arti yang sebenar-benarnya, proporsional, saya pikir
proporsianalitas guru tak harus memiliki kompetensi secara sungguh-sungguh
dibidang yang ia empu, tapi harus mampu menciptakan suatu kondisi surgawi bagi
para anak didik. Dimana murid bisa menaruh cita dan asa-nya, termotivasi dan
bangga memiliki guru.
Ya, barangkali tak banyak orang yang bangga kepada
gurunya sendiri, bisa jadi saya juga demikian. Karena guru bukan lagi sebagai
motivator ulung yang mampu menyihir para muridnya, guru bukan lagi guru yang
asali. Saya tak punya solusi jitu untuk membalik keadaan ini, tapi setidaknya
kita bisa menarik diri kita sendiri dari hiruk pikuk sistem dan kembali menjadi
manusia bernurani. Yang memiliki cita dan mimpi-mimpi, kembali menjadi kecil.
Karena guru sendiri adalah murid dari anak didiknya. Semoga kita bisa kembali
bermimpi... Ah, andai saja.
BUSRI TOHA





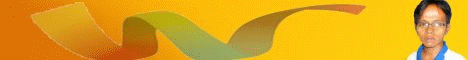


KOMENTAR