Transaksijual beli suara tidak akan pernah menyejahterakan rakyat. Komitmen membangunkeutuhan bangsa adalah kewajiban setiap bangsa berdara...
BELAKANGAN, mesin politik masing-masing partai
politik (Parpol) semakin digerakkan dan dipanaskan. Persaingan antara calon
legislatif terus memanas. Bagai bara api dalam sekam tetapi sudah keluar dan
berkobar. Berbagai cara untuk meraup suara rakyat dilakukan hingga lupa jalan halal
dan menjalankan praktek haram (membeli suara).
Beberapa hari lalu, saya
berjalan-jalan menyusuri rumah-rumah warga. Terutama orang tua atau pemuda yang
memiliki hak memilih, sesuai dengan undang-undang. Berbagai perbincangan
diantara masyarakat sempat saya rekam dalam otak dan mencoba memberikan pemahaman.
Kesimpulan sementara, masyarakat beranggapan bahwa pesta demokrasi (Pemilu)
adalah pesta rakyat menerima uang dari caleg atau Parpol pengusung caleg
tersebut.
Kesimpulan sementara ini barangkali
tidak terlalu keliru. Sebab, selama ini memang rakyat sulit mendapatkan
kesejahteraan. Janji politik tahun-tahun sebelumnya tidak terbukti. Jalan rusak
tetap saja tak diperbaiki. Ekonomi kerakyatan hanya menjadi jargon belaka.
Yatim piatu dan anak terlantar tetap dibiarkan.
Kenyataan itulah, membuat masyarakat apatis terhadap Pemilu.
Sehingga tidak heran jika muncul istilah, jika tidak ada uang tidak akan
memilih. Alasannya cukup sederhana, karena ketika terpilih kelak sebagai wakil
rakyat tidak benar-benar mewakili rakyat tetapi mewakili diri sendiri, famili
atau golongan Parpol saja.
Suatu ketika, saya jalan-jalan lagi ke salah satu kampung dan
banyak berkomunikasi dengan warga. Dalam perjalanan, saya melihat banyak sekali
spanduk dan baliho bertebaran di pinggir jalan. Baliho itu berisi gambar caleg
plus dengan parpol pengusung. Ada yang menggunakan penyangga berupa batang
bambu. Yang menarik perhatian saya, justru ada yang langsung di paku pada pohon.
Saya tidak akan menekankan bahwa itu sudah melanggar
undang-undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 tahun 2013 tentang aturan
pemasangan atribut kampanye, termasuk larangan memasang baliho di pohon. Pasal
17 Peraturan KPU Nomor 15/2013, menyebutkan alat peraga kampanye tidak
ditempatkan di rumah ibadah, rumah sakit, gedung pelayanan kesehatan, gedung
pemerintah, sekolah, jalan protokol, sarana prasaran publik, taman dan
pepohonan.
Petanyaannya, mengapa saya tidak akan menekankan pada
larangan PKPU itu? Sebab, saya yakin bahwa semua caleg sudah mengerti tentang makna
menghargai lingkungan, alam, dan pepohonan. Saya hanya tidak habis pikir,
mengapa pohon yang ”tidak mengerti apa-apa” harus menjadi korban dengan di paku
sedemikian rupa!
Siapapun, akan mengerti bahwa pohon adalah makhluk Tuhan.
Suatu saat, saya bertemu dengan anak kecil. Waktu itu, saya mencoba akan
membunuh semut yang berseliweran di emperan rumah anak kecil itu. ”Mas, jangan
di bunuh semut itu. Kasihan, semut itu juga punya keluarga,” kata anak itu
kepada saya.
Saya terkaget-kaget mendengar jawaban anak itu. Semua makhluk
diciptakan berpasang-pasang, bukan hanya makhluk bernama manusia. Makhluk lain
pun memiliki pasangan. Hati manusia akan sakit ketika pasangannya disakiti.
Pohon adalah makhluk Tuhan.
Kita memang tidak tahu karena tidak tampak apakah pohon itu
berpasangan atau tidak. Tetapi jika berpasangan, dan diibaratkan kepada diri
kita sendiri, apakah tidak sakit jika harus mengalami penderitaan karena dipaku
oleh caleg karena hanya ingin nampang itu? ”Wallahu’aimun bidzatis sudur (Allah
jualah yang mengetahui semua yang mempunyai hati)” kata KH Abdurrahman Wahid
atau Gus Dur.
***
Ketika sampai di perkampungan itu, beberapa warga berkumpul.
Bukan karena kedatangan saya, tetapi memberikan penghormatan kepada tamu yang
datang adalah keharusan. Penghormatan yang luar biasa. Mungkin saja, mereka
berprinsip siapapun tamu yang datang, selama datang baik-baik, harus dihormati.
Seperti biasa, musim pesta demokrasi seperti sekarang ini,
pembicaran tidak lepas seputar Pemilu Legislatif. Masing-masing diantara mereka
membicarakan caleg A dan caleg B. Partai C dan Partai D. Mulai dari karakter
caleg, latar belakang pendidikan, nilai perjuangan yang dilakukan selama ini,
hingga seputar bagi-bagi uang. Semua mengalir bak air di sungai.
”Saya tidak akan memilih jika tidak ada uangnya,” begitulah
celetuk yang saya dengar dari perbincangan mereka. ”Sebab, ketika mereka
terpilih kelak, toh akan lupa juga kepada kita. Janji hanya janji, tak pernah
ditempati. Lebih baik ambil sekarang uangnya,” imbuh orang tadi.
Dalam konteks ini, mereka atau masyarakat secara umum tidak
bisa sepenuhnya disalahkan. Tidak bisa menilai bahwa masyarakat telah terjebak
dengan politik praktis. Munculnya politik transaksional (jual beli suara)
karena memang diajarkan oleh pelaku politik sendiri. Sadar atau tidak, itu
pelajaran yang diterapkan lama kepada masyarakat. Masyarakat dininabobokan
dengan janji dan menebar uang. Misalnya, janji memperbaiki jalan tetapi
nyatanya tidak terbukti. Janji menyejahterakan rakyat, tetapi buktinya rakyat
tetap sengsara.
Pada waktu yang hampir mendekati 9 April 2014 ini, saya hanya
ingin menggugah semua kalangan baik politisi maupun rakyat, yang selalu menjadi
objek dalam politik agar sadar dan menyadari, bahwa politik transaksional atau
mony politic bukan pendidikan politik yang mencerdaskan.
Masyarakat bukanlah objek politik. Suara rakyat adalah suara
Tuhan. Masyarakat (setidaknya pandangan saya) tidak akan mau satu suara hanya
dihargai uang receh puluhan ribu tetapi kemudian hari terus dilupakan dan
ditinggalkan. Hak hidup sejahtera sesuai amanat UUD 45, tidak diperjuangkan.
Sementara, para pelaku politik tidak perlu
menghambur-hamburkan uang dengan bentuk ”shodaqoh” uang. Kini, bukan saatnya
lagi kapitalisme politik digerakkan. Menepati janji, sebagaimana kata Nabi,
janji adalah hutang, adalah lebih berharga dan akan lebih terhormat di mata
masyarakat. Hargai suara rakyat bukan dengan cara mony politic yang
picik. (*)
OLEH BUSRI TOHA





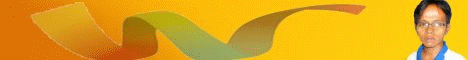


KOMENTAR